Novel oleh: Isrina Sumia
Sebelum aku beritahu benar atau tidaknya aku menikah dengan Bowo. Mari kita masuk ke lorong waktu terlebih dulu.
Tepatnya di tahun 2001 di minggu pertama bulan Juli. Hari pertama aku menginjak kelas dua SMA. Hari yang paling dinantikan oleh banyak siswa, hari pertama masuk sekolah. Terlebih mereka yang baru saja lulus di tingkat SMP dan masuk ke SMA Putra Negara. SMA Unggulan pada zamanku dulu. Tapi tidak denganku, yang hari itu lari terbirit-birit karena terlambat. Jejeran ojek sepeda sudah terlihat kosong, pasti sudah terisi penuh oleh pelajar yang sama terlambatnya denganku.
Akhirnya aku memilih berlari, lumayan setidaknya sambil membakar kalori berat tubuhku yang sudah memasuki angka 60 kilo itu. Aku terus berlari kecil menyusuri jalan masuk menuju sekolah yang jaraknya kurang lebih sekitar lima ratus meter itu.
Saat itulah aku melihat seorang murid yang sedang dipalak oleh beberapa siswa STM yang wajahnya sudah akrab denganku ketika mereka tawuran.
Tiga siswa STM itu terlihat mengepung anak sekolah berseragam putih abu di balik tiang listrik. Saat kulihat, aku memilih melintas. Tapi hati sudah kadung teretas, tak tega.
Sepanjang pengetahuanku, anak-anak STM adalah anak pemberani yang hanya berani melawan lelaki. Tak berani mereka melawan perempuan, apalagi bertanding. Jadi kuputuskan saja untuk berbalik, dan berteriak ke arah mereka.
“HEH!” Aku berteriak lantang, dan ketiga anak STM dengan seragam putih kusam yang tak dimasukkan bajunya itu melihatku aneh. Aku mendekat. Sambil membusungkan sedikit dada, karena aku berhijab bagian depan itu cukup aman. Kudekati mereka, dan anak berseragam putih abu yang dipalak itu pun juga diam. Uang lima belas ribu terliihat ditangannya seperti hendak dia serahkan. Lalu dirampas.
“Ehhh! Balikin!” lanjutku, tak peduli mungkin aku akan terlambat sekolah atau tidak.
“Siapa sih lu Anjiing!” jawab mereka.
“Ya gua pelajar lah! Balikin atau gua teriak nih! TOLONG ADA TUKANG PALAK!”
“Betina tai!” rutuk mereka sambil melempar uangnya. Kucomot dari jalan terus memberikan pada pelajar berseragam baru itu. Kemejanya masih putih bersih, tak sama denganku yang sudah kecokelatan.
“Terima kasih Bu Haji!” Ibu haji! Enak banget dia manggil Ibu, emang tampangku setua itu? Tapi mungkin dia bilang begitu karena badanku yang lemu. Setelahnya kami pun berjalan beriringan.
“Siswa baru?” Aku menebak karena kemejanya masih menebarkan aroma seragam baru yang sering kucium di pasar Lontar tempat Ibuku berjualan makanan jajanan pasar.
“Iya,” jawabnya. Suaranya begitu berat, tebal terdengar.
“SMA apa STM?”
“SMA.”
“SMA PUTRA?”
“Iya.”
“Sama donk! Ya udah lari, kita udah telat tahu!” kataku sambil berlalu meninggalkannya, sedang lelaki bertas selempang hitam dengan celana dan kemeja yang terlihat masih baru itu terlihat santai.
Tiba di gerbang sekolah, aku tak langsung masuk. Karena baru saja kulihat Pak Narto guru Bahasa Indonesia yang sekaligus merangkap sebagai Guru BK itu baru saja memaksa anak-anak yang baru datang di lapangan untuk push up dan sit up.
Belum lagi, memeriksa perlengkapan sekolah yang wajib digunakan siswa SMA PUTRA. Di antaranya Dasi, sabuk, kemeja bersih, celana dan rok yang tidak ketat, kaus kaki putih bersih, sepatu warna hitam dan terakhir Pin sekolah. Jika salah satu tidak dipakai maka setiap siswa akan mendapat Point kesalahan yang akan diakumulasi untuk penilaian kedisiplinan.
Saat mengintip, tiba-tiba siswa tadi yang bertemu denganku melintas. Kutarik kerah bajunya sampai dia terjungkal. “Ada Pak Narto!” kataku.
“Ya udahlah namanya juga telat.”
“Ya ampun, kamu aja nggak pakai Pin sama Dasi.”
“Dia keluarin dari dalam tasnya kemudian dia pakai dasi itu.”
“Pin mana?”
“Nah hilang!”
“Udah telat nggak pakai Pin, nggak selamet. Ayo ikut!” kataku, tapi dia malam diam melotot melihatku.
“Ke mana?”
“Udah ikut aja!” balasku lagi. Siswa yang kukira adik kelasku itu kemudian mengekor di belakang. Sampai tiba kami, di pagar halaman STM yang tembus langsung dengan pekarangan belakang SMA Putra.
“Lagi upacara, dah tunggu aja. Nanti malah ketahuan!” katanya memberi saran, seperti dia lebih tahu dengan sudut geografis sekolah. Aku menatap sinis ke arahnya, sambil menumpuk bangku-bangku tua agar aku bisa naik.
“Kalo nggak ikut upacara malah lebih bahaya!” balasku.
“Upacara sebentar lagi, pas bubar, kondisi lapangan crowdid, nah pas itu kita masuk ke kelas, jadi nggak ketahuan. Lumban sama Narto punya mata elang buat nangkap kita.”
Iya juga, dia sepertinya lebih tahu banyak dariku. “Kamu anak kelas berapa sih?” Dia malah menyeringai.
Kuperhatikan dengan seksama dari atas bawah penampilannya. Ada yang baru saja membuatku sadar, jika wajahnya begitu mirip dengan Pacey dalam serial Dawson Creek. Serial Amerika yang sedang ramai selain boyband Westlife, M2M, dan Britney Spears. Namun, kemeja dan celananya baru, begitu pun dengan kaus kaki juga sepatunya. Atau mungkin, dia kakak kelas? Ah entahlah. Aku tak berani menebak.
Kami duduk di atas konblok yang sudah rapuh dan berjamur ditemani dedaunan kering sambil menikmati jalannya upacara di balik dinding batako tua yang sudah hampir rubuh. Tak ada yang dia lakukan kecuali diam, sedang aku memilih untuk membuka buku tulis matematikaku yang masih tersisa lembaran kosongnya sejak kelas satu.
“Masih dipake buku kelas satu!” katanya.
“Sengaja cari yang tebel,” balasku.
“Kalo gua udah gua buang!” timpalnya, aku tak jawab lagi. Tak percaya diri berbicara lama-lama dengan lelaki berparas pernarupa sepertinya. Kulit putih, tubuh harum, bersih, hidung mancung dan bulat, alis tebal, sempurna!.
“Udah selesai tuh!” katanya, dan selanjutnya buru-buru kami bersiap naik.
“Ladys first,” jawabnya.
“Nggak kamu aja dulu.”
“Kenapa?” tanyanya curiga.
“Ya nggak apa-apa!”
“Nggak pake daleman ya? Hahahahha!” Dia terpingkal-pingkal sambil naik.
“Enak aja!” sungutku, sambil menyusulnya. Saat hendak melompat, anak itu sudah berlari sambil melambaikan tangan.
Buru-buru aku naik ke tangga mengikuti rombongan anak-anak yang baru saja selesai mengikuti upacara kemudian masuk ke dalam kelas.
2-4 itu kelasku. Kelas buangan, katanya. Anak-anak nakal yang memiliki point terbanyak berkumpul di sana. Namun, bagiku ini adalah kelas yang akan memerdekakan aku dari anak-anak unggulan yang kaku dan sedikit congkak di 2-8. Ya, aku lebih nyaman berkumpul dengan anak-anak bergajulan tanpa predikat pintar atau unggulan. Karena sebelumnya aku ditempatkan di kelas satu unggulan, dan itu justru semakin membuatku stress dan tertinggal.
Aku berjalan santai menuju kelas 2-4 dan setiba di sana. Aku tercengang. Kursi depan blash kosong. Semua anak-anak lebih memilih duduk di belakang, jejeran kursi depan kosong begitu saja.
Duduk aku di depan berhadapan persis dengan papan tulis. Sebelah kanan kiriku masih kosong, juga teman sebangkuku pun belum ada. Kuperhatikan satu per satu wajah-wajah mereka dan tiada satu pun yang kukenal. Semua teman di kelas satuku berhasil masuk ke kelas dua unggulan dan hanya aku yang terbuang.
Lalu beberapa saat kemudian, ada siswa lainnya yang masuk ke kelas. Mataku langsung terbelalak, dan tercengang, dia anak lelaki yang baru saja bareng denganku, yang wajahnya mirip dengan Joshua Jackson dalam serial Dawson Creek.
“Bowo! Bowo!” kedatangannya di sahut banyak perempuan yang duduk paling belakang, juga beberapa teman lelakinya yang menyebut, “Si Bos dateng!” kata mereka.
Aku benar-benar tidak pernah berpikir, jika dia akan menyapaku demikian. “Bu Haji!” katanya sambil mengetuk meja belajarku, kedua pipiku terasa hangat dan tengkukku bergidik parah. Bowo namanya, dia melintas kemudian duduk di bangku belakang yang ternyata sudah disiapkan oleh teman-temannya.
Tak lama kemudian, Wali kelas kami masuk ke dalam kelas. Guru Bahasa Indonesia yang terkenal lembut, baik hatim dan tidak sombong nan cantik bernama Haryati. Wanita berambut merah itu langsung duduk di tempatnya, dan sebelum memulai dia memandangi satu per satu anak-anak asuhnya di sekolah, kemudian bola matanya berhenti pada beberapa bangku kosong di depan.
“Ini kok nggak ada yang mau duduk di depan sih?” tanyanya sambil berjalan.
“Meyna! Pindah ke depan! Kamu ngapain cewek sendirian di belakang!”
“Eyaaa Bapoeek, pindah Poek!” sahut yang lain, seperti sudah akrab.
“Nggak ah Bu! Aku suka panik kalo duduk depan!” timpal Meyna atau Bapoek.
“Maju-maju!” kata Bu Haryati pada beberapa siswa yang duduk di deretan kursi nomor dua. Dengan wajah terpaksa akhirnya mereka mau.
“Satu lagi kosong nih!” tambah Bu Haryati, maksudnya teman sebangkuku.
“Siapa yang mau?”
“Yati maju!”
“Nggak ah Bu!” balas Yati.
“Nita!”
“Takut Bu!”
“Ya ampun, kalian ini!”
“Angga maju nggak!”
“Jangan saya Bu.”
“Saya aja Bu!” Suara tebal itu tiba-tiba saja merangsang kesendirian dan perasaan terbuangku. Mataku mendelik, dan tak lama benar saja. Bowo yang meminta untuk duduk di sampingku, saat dia duduk dia tersenyum memandangku, terus meledek, “Bu Haji nggak pake daleman!” ledeknya kemudian terpingkal.
-II-
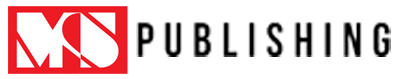

Wpbingo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam fringilla augue nec est tristique auctor. Donec non est at libero vulputate rutrum. Morbi ornare lectus quis justo gravida semper. Nulla tellus mi, vulputate adipiscing cursus eu, suscipit id nulla.